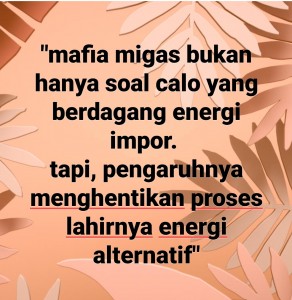-Yanuar Rizky-
elrizkyNet, 8 Januari 2020:
Presiden Joko Widodo mengatakan jika uni eropa terus melakukan kampanye negatif terhadap sawit Indonesia, maka kita akan konsumsi sendiri. Hal itu dikatakan Presiden ketika meluncurkan produk B30 oleh Pertamina.
Tekad kuat untuk melakukan hilirisasi energi terbarukan dari perkebunan sawit harus menjadi sikap yang konsisten dilakukan. Inilah, inisiatif aksi nasional dalam mengubah permainan defisit neraca migas, sekaligus sebagai amunisi di arena perang dagang global di masa depan.
Persoalan hilirisasi bukanlah isu baru. Tapi, godaan terbesar pembagunan industri hilir adalah ketika harga sumber daya mentah (komoditas) primernya tengah tinggi.
Kita bisa lupa akan industrialisasi (hilir), dan pragmatis melakukan ekspor komoditas primer.
Godaan itu datang dari China. Dimana, dalam pertarungan perang dagang dengan Amerika Serikat, negara tirai bambu menyerang paman sam dengan mengerem importasi kacang kedelai (soy bean)
Kebutuhan akan kacang kedelai di China digantikan dengan memperbesar importase palm oil (sawit). Tentu, ini bukan dengan tujuan pengganti bahan makanan tahu yang juga terkenal di China.
Niat Tiongkkok ini pernah diutarakan Perdana Menteri China Li Keqiang kepada Presiden Jokowi di Bogor di awal Mei 2018. Dimana, negaranya bersedia meningkatkan kuota impor sawit dari Indonesia.
Tidak hanya itu, China sebagai negara pengimpor sawit ke 2 setelah India di tahun 2018, mengeluarkan kebijakan di tahun 2020 kuota impor sawit ke negeri tirai bambu akan dibuka lebih luas sebagai respon atas kebijakan tarik rem tangan impor kacang kedelai dari Amerika Serikat.
Belajar dari Batubara
Tahun 2006, paska tekanan pasar keuangan di tahun 2004-2005 ke China yang dipicu harga minyak tinggi, Tiongkok mengambil kebijakan impor batubara seluas-luasnya.
Saat itu, harga batubara terdongkrak naik. Banyak bermunculan orang kaya baru pemilik lahan batubara (IUP) di tanah air. Pasar ekspor kinclong dari batubara. Neraca perdagangan juga mentereng.
Pada periode 2006-2008, kita tak pernah bicara hilirisasi batubara. Kita juga tertolong oleh harga minyak yang kembali turun. Defisit neraca migas (energi konsumsi) tertutupi positifnya neraca ekspor batubara.
Lalu, kemudian di tahun 2008 era perang moneter global memasuki babak baru paska krisis gagal bayar kredit perumahan di bursa wall street.
Kondisi ini memaksa The Fed untuk bermain di zona bunga acuan rendah, itu artinya inflasi harus berada dalam zona rendah pula.
Dengan kata lain, babak perang moneter 2004-2005 dengan menghantam Tiongkok dengan inflasi tinggi melalui politik harga minyak telah jadi bumerang bagi Amerika.
Dan lalu, di tahun 2009 paska kebijakan QE (Quantitative Easing) dirilis The Fed, yang berjalan beriringan dengan insentif energi alternatif, dunia dikejutkan dengan digunakannya shale gas di industri Amerika Serikat.
Kehadiran shale gas telah menghantam harga gas di pasar dunia. Penurunan permintaan gas alam yang diakibatkan substitusi pemakaian shale gas di Amerika.
Bagaimana dengan China? Di titik ini, kita baru memahami kenapa Tiongkok sebelumnya agresif menyerap impor batubara, meski mereka pun memiliki sumber dayanya.
Ternyata, China membangun hilirisasi batubara, yaitu menjadi gas (gasifikasi). Sehingga, perang dagang di zona harga energi rendah (alternatif) juga dimiliki industri di China.
Petaka datang di harga batubara, karena tekanan perang dagang barat menyoroti gasifikasi batubara tidak ramah lingkungan.
China tak bergeming, karena hilirisasi telah mereka lahirkan menjadi gas pakai.
Tapi, di sisi mata uang lain sentimen negatif ramah lingkungan batubara kita rasakan. Pasar ekspor energi primer batubara mengempis dan harganya pun jatuh.
Itulah awal masalah kita hari ini, yaitu tekanan neraca perdagangan yang dirasakan sejak 2011, dan merembet ke neraca pembayaran di 2012 akibat tekanan sentimen penghentian QE The Fed di pasar keuangan.
Saat tertekan, kita beramai-ramai berwacana bahwa kesalahan kita tidak melakukan hilirisasi.
Kita pun berandai-andai, seumpama kita hilirisasi sendiri gasifikasi batubara di masa lalu, mungkin tidak elastisnya harga gas alam di dalam negeri tidak akan terjadi.
Ya, karena tak ada energi substitusi, harga gas alam di hulu di pasar domestik tidak elastis ke harga internasional sebagaimana negara lain.
Dalam pemahaman saya, mafia migas bukan hanya soal calo yang berdagang energi impor. Tapi juga kemampuannya menghambat tidak lahirnya energi alternatif sebagai bahan baku subtitusi.
Kalo melihat ini, rasanya tak berlebihan untuk kita menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden agar sekali ini hilirisasi sawit, bahkan menuju B100, jangan kendur dan layu sebelum berkembang hanya karena godaan ekspor sawit kembali terbuka di tahun 2020.
Energi Hijau Perang Masa Depan
Saat perjalanan dinas studi banding ekosistem pertanian di Amerika Serikat, saya sempat bertemu lobbyist dari asosiasi petani jagung dan kacang kedelai.
Satu sisi, petani Jagung diuntungkan oleh kebijakan perang dagang Trump. Walaupun, sisi lainnya petani kacang kedelai merasa dirugikan.
Di Amerika Serikat, jagung adalah rantai yang menjadi kunci ketahanan pangan. Karena, masyarakatnya pemakan daging (protein), maka pakan ternak dari jagung adalah kunci.
Digenjotnya produktifitas Jagung menyebabkan pasokan juga berlebih. Hal ini, melahirkan pemanfaatan jagung (juga kacang kedelai) untuk energi hijau. Ya, sama seperti sawit.
Negara terdekat Amerika Serikat, Brazil sama dengan Indonesia adalah penghasil sawit.
Singkatnya, terjadi perang sumber energi hijau juga, dimana sawit dengan rasio penggunaan lebih sedikit dari jagung dan kacang kedelai akan mengancam petani paman sam dalam hilirisasi kebunnya untuk energi hijau.
Dalam kesempatan itu, saya sempat menanyakan untuk apa bahan bakar nabati (green fuel), bukankah disini ekosistem mengarah ke mobil listrik?
Jawaban yang saya terima adalah politik ekonomi Amerika Serikat mendorong tumbuhnya mobil listrik, tapi tidak akan membunuh industri mobil berbahan bakar.
Alasannya, mandat konstitusi soal penyerapan lapangan kerja. Dimana, industri mobil listrik akan menghilangkan banyak komponen (spare part) dari mobil berbahan bakar.
Hilangnya industri komponen, diyakini akan menimbulkan ledakan pengangguran. Itu sebabnya, isu lingkungan di energi fosil diganti dengan energi hijau (nabati). Bukan, mengganti seluruhnya dengan energi baterai (listrik).
Posisi ini, menurut hemat saya, ditambah sinyal aksi agresif China akan impor sawit, menunjukan permainan perang dagang dan moneter di depan kurva adalah hilirisasi kebun menjadi industri energi hijau (nabati).
Jadi, rasanya kita sudah cukup belajar dari pengalaman era booming ekspor batubara yang ujungnya menjadi bara bagi defisit neraca perdagangan dan pembayaran di kemudian hari.
Sinyal tanda-tanda jaman soal ramah lingkungan yang dipakai membonsai batubara juga tampak di sawit. Ini bisa kembali akan menjadi masa kelam neraca ekspor komoditas primer (kembali) kita rasakan.
Presiden Jokowi harus tegas dalam sikap, tak ada tawar menawar dan jangan mudah tergoda pragmatisme ekspor sawit hanya karena ekonomi melemah.
Presiden harus memimpin hilirisasi industri sawit dan tagline “kita konsumsi sendiri” dengan kaca mata kuda melihat di depan kurva dunia setelah tahun 2021.
Salah satu yang patut didorong adalah komersialisasi teknologi katalis merah putih dari labotarium Teknik Kimia ITB (Institut Teknologi Bandung).
Saat ini masih B30, yang merupakan blending (mencampur) sawit (cpo) dengan metanol, sehingga 30 persennya bisa dari energi hijau dan 70 persennya energi fosil.
Jika prosesnya dirubah, dimana sawit (ipo) dicampur dengan katalis merah putih, maka akan menghasillan B100.
Hal itu pernah saya liat lab riset katalis merah putih di ITB. Juga melihat sampel bensin, diesel dan avtur (B100) yang dihasilkan dari reporoses (refinery) katalis merah putih dengan minyak sawit (ipo). Youtube: Apa itu Katalis Merah Putih
Komersialisasi riset menjadi pembangunan pabrik katalis merah putih akan mensubstitusi impor produk petrokimia.
Kita harus yakin, arah baru agrokimia, yaitu industri katalis sepaket dengan pembangunan kilang energi hijau.
Hanya saja, isu pembangunan kilang (refinery) energi hijau tampaknya berpotensi dihadapkan kepada harga sawit yang tinggi sebagai bahan baku
Narasi importir mengajukan pragmatisme bahwa akan tetap lebih murah tetap menggunakan energi fosil, meski impor.
Ruang pembangunaan opini harga rendah energi fosil rendah kembali terbuka.
Dampak, kembalinya bank sentral negara maju ke zona inflasi rendah di semester dua 2019 menekan turun harga minyak fosil. Sehingga, penurunan harga jual BBM (Pertamina) juga terbuka.
Tapi, bacalah di depan kurva negara maju. Di sisi mata uang lainnya, dunia bersiap ke hilirisasi energi hijau. Itulah makna dibalik naiknya kembali harga sawit saat ini, karena dipicu impor China.
Agar tidak salah baca dan menjadi arah yang keliru terulang, maka pelajaran batubara harus jadi poin penting dalam membaca peta energi hari ini di masa depan.
Pembangunan industri energi hijau harus mulai dikerjakan, bukan diwacanakan. Kalau bukan kita, lalu siapa?. Kalau bukan sekarang, lalu kapan?
Sejarah ditentukan oleh langkah hari ini. Karena, investasi adalah transaksi hari ini untuk masa depan.
#enjoyAja,
-yanuar RIZKY, WNI